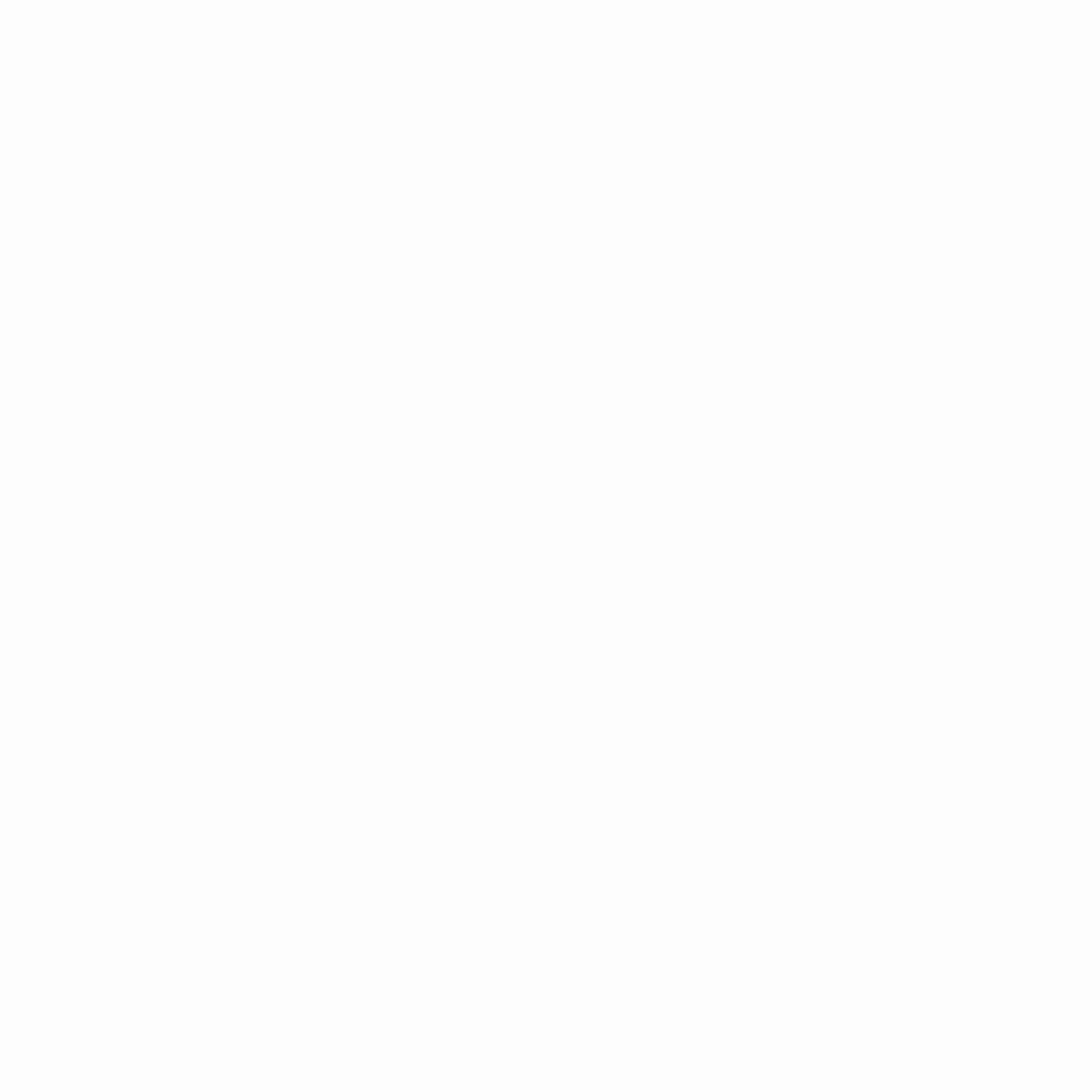
Cancel Culture di Antara Satir dan Komedi
Komeng jadi sasaran baru cancel culture
Beberapa waktu lalu, nama komedian Komeng mencuat jadi trending topic. Salah satu materi guyonnya memicu kontroversi di jagat maya.
Dalam sebuah kisah yang ditayangkan di televisi, komedian bernama asli Alfiansyah Bustami tersebut berperan sebagai seorang ayah yang memiliki seorang putri. Di salah satu bagian, Komeng pun beradu jenaka dengan Marshel Widianto, lawan mainnya ketika itu.
“Bapak mau ke mana?” ujar Marshel Widianto pada Komeng yang hendak keluar dari set.
“Saya mau jagain anak saya, takut ada yang ngintip orang lain. Daripada orang lain yang ngintip mending bapaknya yang ngintip,” kata Komeng.
Menanggapi hal tersebut, opini publik pun akhirnya terbelah dua.
Sebagian menilai ujaran tersebut sebagai komedi satir, terinspirasi dari isu pelecehan seksual yang betulan ada di ruang publik.
Sementara itu, tak sedikit pula yang menganggap guyon tersebut offensive dan insensitive; memicu kemarahan publik dan terkesan permisif terhadap kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang selalu naik tiap tahun.
Tea! ok im done pic.twitter.com/fc4bfuDAma
— AREA JULID (@AREAJULID) January 11, 2022
Pisau bermata dua
Nggak butuh waktu lama, serangkaian cuitan pun bermunculan. Meski tak sedikit yang membela, Banyak pula yang menyerang Komeng.
Mereka mengungkapkan rasa marah dan jijik sambil meminta akuntabilitas pada komedian yang sudah berkarir sejak era 90-an tersebut. Nggak tanggung-tanggung, bahkan ada yang ingin Komeng di-cancel saat itu juga. Maklum, emosi negatif memang gampang menular lewat media sosial.
Namun perlu dipahami pula bahwa, meski bisa jadi sarana keadilan sosial, cancel culture juga bisa jadi senjata intimidasi massal. Komedian sekelas Kevin Hart dan Dave Chapelle pernah jadi korbannya.
Komedian senior Amerika Serikat, Steve Harvey pun angkat suara soal isu tersebut. Ia mengaku tak lagi ingin tampil di panggung stand up comedy karena risiko dampak cancel culture yang begitu besar.
“Satu-satunya jalan aku akan melakukan pertunjukan stand up comedy spesial adalah ketika aku sudah ada di ujung karir televisiku,” ujarnya dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.
“Kita ada di era cancel culture. Tak akan ada komedian yang didukung sponsor yang bisa berbicara bebas. Chris Rock tidak bisa melakukannya. Kevin Hart tidak bisa melakukannya. Cedric the Entertainer tidak bisa melakukannya. D.L. Hughley tidak bisa melakukannya. Aku tidak ingin memperpanjang daftar itu,” lanjutnya.
“Satu-satunya komedian yang bisa berekspresi bebas di panggung adalah Dave Chapelle karena ia tidak didukung sponsor. Ia didukung sistem berlangganan.”
Cancel culture pun tak selalu berdampak negatif. Sebagai contoh, majalah Vogue Amerika Serikat sempat di-call out karena dianggap kurang merepresentasikan talenta kulit hitam (fotografer, editor, model).
Hal ini memicu tagar #VogueChallenge, dimana para talenta kulit hitam membuat cover Vogue versi mereka sendiri; menjadi trigger untuk berkreasi dan mendorong semangat keberagaman di dunia fashion.
Cancel culture: context over content
Lantas, bagaimana kita harus bersikap ketika merespon guyonan Komeng atau isu sejenis?
Sebagai pentonton, ada dua langkah yang kita bisa ambil.
Yang pertama, kita harus memahami bahwa karya dan kreator adalah dua entitas yang berbeda; sebuah karya seni tak selalu merepresentasikan kreatornya sebagai seorang manusia.
Umpamanya begini: misalkan lo menemukan sebuah buku yang tidak mencantumkan nama penulisnya. Setelah dibaca, lo mendapati bahwa buku tersebut adalah sebuah masterpiece. Jika lo mengetahui bahwa buku tersebut ternyata ditulis oleh seorang copet, apakah kualitas buku tersebut jadi jelek? Tentu tidak.
Dalam konteks komedi, perlu dipahami pula bahwa humor adalah coping mechanism yang paling umum buat banyak orang untuk menghadapi keresahan atau bahkan trauma.
Tak jarang, kegelisahan tersebut pun bertransformasi menjadi banyolan satir nan sarkas. Lawakan yang keluar mungkin nggak selalu lucu atau bahkan menyinggung perasaaan penonton. Meski begitu, ada pesan dan tujuan baik di baliknya.
Yang kedua, kita harus mencari tau dan mencerna tujuan dan konteks penuh karyanya.
Jika sang kreator punya agenda misoginis dan berniat untuk menyusupkan tujuan gelap dalam karyanya supaya publik terbiasa dan memaklumi aksi serupa, maka kita patut menuntut pertanggungjawaban; lewat edukasi dan mengingatkan.

